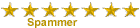Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.
Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.
Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis).
Sejarah telah usai,” teriak Francis Fukuyama. Seruan itu tepat didengungkan setelah komunisme di Uni Sovyet runtuh lewat program glasnost dan perestroika dan hampir bersamaan dengannya China juga mulai membuka ekonomi nasionalnya. Komunisme dan model ekonomi-terpimpin yang awalnya begitu gagah dan tangguh melawan kapitalisme dan demokrasi liberal, tiba-tiba jatuh tersungkur tak bangkit lagi. Perang Dingin usai sudah. Lewat seruan Fukuyama itu genderang kemenangan sudah ditabuh. Hingga kini, Demokrasi Liberal dan Kapitalisme menjadi pemenang tunggal peradaban. Lantas, seperti Fukuyama ungkapkan, tugas manusia modern menjadi semakin ironis; hanya merawat dunia yang laksana museum tambo. Tidak ada lagi gairah, perlawanan dan antidot. Cerita tentang sosok Che sang petualang revolusi sudah harus dikubur dalam-dalam. Kisah heroik Lenin hanya tinggal sejarah di buku-buku, keberanian Usamah bin Laden cukup hanya tersemat di kaos-kaos anak muda saja. Narasi besar tentang revolusi dan perlawanan massa hendak diakhiri, tetapi narasi besar yang lain, yang berwujud demokrasi liberal dan kapitalisme harus tetap dibiarkan melenggang. Lantas seorang sastrawan Indonesia, Gunawan Mohamad, mengamininya dengan menuliskan sebuah buku; Setelah Revolusi Tak Ada Lagi.
Benarkah Demokrasi Liberal dan kapitalisme adalah satu-satunya kebenaran? Benarkah tidak akan ada perlawanan terhadap dominasi “Two Towers” (baca: demokrasi liberal dan kapitalisme) ini? Benarkah ini sistem yang terbaik? Benarkah kapitalisme dan demokrasi liberal tidak akan mengalami krisis dan kontradiksi internalnya?
Petaka Demokrasi Liberal
Krisis dan kritik terhadap model demokrasi liberal sebenarnya sudah jauh hari diingatkan oleh beberapa kalangan. Kritik terhadap demokrasi datang dari tradisi Marxisme – utamanya Lenin – yang menyebut bahwa demokrasi sebenarnya adalah siasat kaum borjuis. Lenin mengolok demokrasi liberal sebagai kediktatoran kaum borjuis (the dictatorship of borguise), dimana instrumen dan sumberdaya kekuasaan yang berupa hukum, ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir kelompok borjuis saja. Karena itu, alih-alih berpihak kepada kesejahteraan proletar, model demokrasi ini hanya akan menghasilkan model politik massa mengambang serta lahirnya oligarkh dan teknokrat politik yang enggan berbaur dan menjawab tuntutan serta penderitaan rakyat.
Tidak hanya pada tradisi marxisme, kritik terhadap demokrasi liberal juga datang dari kalangan pendukungnya sendiri. Ironi ini bermula dari teoretisi demokrasi Joseph Schumpeter yang menafsirkan demokrasi hanya terbatas sebagai mekanisme memilih pemimpin melalui pemilu yang kompetitif dan adil. Senada dengan itu, Samuel P. Huntington, sama naifnya dengan Schumpeter, juga menyanyikan nada yang seirama. Bagi Huntington, kualitas demokrasi diukur oleh pemilihan umum yang kompetitif, adil, jujur dan berkala dan partisipasi rakyat yang tinggi selama pemilu. Cita-cita mulia demokrasi direduksi menjadi sebatas hal yang prosedural dan teknis. Akibatnya, demokrasi hanya diwujudkan dalam pemilu. Suara rakyat dibutuhkan dan ditambang hanya ketika pemilu datang. Setelah itu, suara rakyat ditendang dan dikhianati; kebijakan publik tidak lagi memihak rakyat, harga-harga semakin mahal, penggusuran dimana-mana, BBM dinaikkan, pendidikan dan kesehatan dikomersialisasikan, kemiskinan dan pengangguran tetap saja berkembang biak. Demokrasi, dalam cita-cita yang sesungguhnya, perlahan-lahan mati.
Dalam konteks ini kritik Geoff Mulgan terhadap paradoks demokrasi sangat tepat dan jitu. Ada tiga hal pokok dalam kritiknya terhadap demokrasi. Pertama, demokrasi cenderung melahirkan oligarki dan teknokrasi. Bagaimana mungkin tuntutan rakyat banyak bisa diwakili dan digantikan oleh segelintir orang yang menilai politik sebagai karier untuk menambang keuntungan finansial?
Kedua, prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, kebebasan dan kompetisi juga telah dibajak oleh kekuatan modal. Yang disebut keterbukaan, hanya berarti keterbukaan untuk berusaha bagi pemilik modal besar, kebebasan artinya kebebasan untuk berinvestasi bagi perusahaan multinasional, kompetisi dimaknai sebagai persaingan pasar bebas yang penuh tipu daya.
Ketiga, media yang mereduksi partisipasi rakyat. Kelihaian media mengemas opini publik membuat moralitas politik menjadi abu-abu, juga cenderung menggantikan partisipasi rakyat. Ini berujung pada semakin kecil dan terpinggirkannya ‘partisipasi langsung’ dan ‘kedaulatan langsung’ rakyat.
Tidak hanya itu, sesat pikir kaum demokrasi prosedural juga karena ia menyembunyikan fakta tentang negara dan kekuasaan. Negara, seperti kita semua maklum, adalah tempat akses dan relasi ekonomi, politik, hukum berlangsung. Karena itu, sistem demokrasi juga berhadapan dengan masalah ekonomi. Negara dan sistem demokrasi juga berhubungan dengan masalah bagaimana menciptakan kesejahteraan, bagaimana menjalankan dan mengatur finansial sebuah negara. Karena itu negara membutuhkan sebuah persekutuan yang taktis dan cepat. Karena hanya model ekonomi kapitalisme yang tersedia – yang bertumpu pada kekuatan modal besar -, maka demokrasi membutuhkan kapitalisme, begitu juga sebaliknya. Dari sini, persekutuan najis itu mulai tercipta.
Di ujung jalan, tampaknya kapitalismelah yang berkuasa. Atas nama kemajuan dan perdagangan bebas, ia mulai mengangkangi negara. Atas nama pertumbuhan ekonomi, ia mulai menyiasati demokrasi. Lalu muncullah makhluk lama dengan baju yang baru: neoliberalisme. Sebuah makhluk yang mengendap-endap muncul, lalu menjalankan taktik “silent takeover”. Istilah terakhir ini dipinjam dari Noreena Heertz, artinya kurang lebih sebuah penjajahan yang terselubung.
Teror Neoliberalisme
Pada awalnya hanyalah gagasan. Neoliberalisme digulirkan sekelompok intelektual di sebuah dataran tinggi Mont Pelerin di Swiss. Beberapa pemikir, pengusaha dan media ini memperbincangkan dan mengangankan sebuah tata dunia baru yang tanpa tapal batas; sebuah tata dunia baru yang dikendalikan sepenuhnya oleh pasar dan kekuatan modal; sebuah tata dunia yang berjalan tanpa aturan negara; sebuah tata dunia yang meninggalkan negara kesejahteraan a la Keynessian menuju pasar bebas. Neoliberalisme kemudian dikenal sebagai sebuah kendaraan yang mengusung satu proyek besar dunia; globalisasi. Gagasan ini kemudian dengan cepat menjadi sebuah ‘horor global’ ketika ia diadopsi menjadi sebuah tata dunia baru. Ini terjadi setelah administrasi Reagen dan Tatcher mengadopsi gagasan Mont Pelerin Society ini. Setelah itu, hampir semua kebijakan dan lembaga internasional seperti World Bank, IMF dan WTO praktis mengalami perubahan untuk mendukung paham globalisasi.
Paling tidak, ada dua faktor yang mendorong kenapa gagasan tentang neoliberalisme ini dipakai dan diadopsi oleh rejim anglo-america tersebut. Pertama, ada krisis besar dan resesi ekonomi dunia yang utamanya mengenai Amerika Serikat. Krisis ini semacam krisis overproduksi yang menimpa sejumlah perusahaan multinasional dan perbankan yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme negara yang dianut oleh kebanyakan negara-negara dunia ketiga dan negara-negara miskin. Kedua, model negara kesejahteraan (welfare state) mengalami kebangkrutan akibat besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara untuk jaminan sosialnya rakyatnya.
Dengan demikian, kemenangan gagasan neoliberalisme adalah kemenangan bagi perusahaan multinasional dan sejumlah korporasi yang merasa menderita pada jaman kapitalisme negara. Termasuk juga kemenangan bagi negara maju dan sejumlah korporasinya untuk memberi ‘tekanan’ pada negara miskin agar mematuhi doktrin khas neoliberal: liberalisasi-privatisai-deregulasi. Pendeknya setelah jaman globalisasi neoliberal menjelang, maka tapak-tapak imperialisme ini mulai berjalan. Ini bisa ditandai oleh semakin mengguritanya korporasi internasional yang bersiap mencengkeram seluruh kehidupan rakyat.
Noreena Hertz punya gambaran yang menarik, bagaimana suasana yang terjadi setelah dunia berada dalam jaman globalisasi neoliberal ini. Menurutnya, selama berlangsungnya era globalisasi yang ditandai oleh kebijakan privatisasi, deregulasi dan liberalisasi perdagangan, dan kemajuan teknologi komunikasi, terjadi pergeseran kekuasaan. Kekuasaan pasar dan korporasi global tiba-tiba tumbuh mejadi monster yang bisa mengancam keberadaan negara dan demokrasi rakyat.
Dalam data yang dimiliki oleh Noreena tercatat ada 100 perusahaan multinasional terbesar mengontrol 20% aset asing global, 51 dari 100 negara terbesar dunia adalah perusahaan, hanya 49 yang merupakan negara bangsa. Penjualan General Motor dan Ford lebih besar daripada GDP seluruh negara-negara sub-sahara Afrika. Aset IBM, BP dan General Electric lebih besar daripada kebanyakan negara-negara kecil; dan Wal-Mart, pengecer supermarket Amerika Serikat, memiliki penghasilan yang lebih besar daripada negara-negara Eropa Timur dan Tengah termasuk Polandia, Republik Ceko, Ukraina, Hungaria, Rumania dan Slovakia. Karena itu barang-barang yang dikonsumsi manusia hampir berada dalam genggaman korporasi ini. Di tangan mereka-lah kehidupan dunia kini dipertaruhkan.
Kekuasaan korporasi yang sangat hegemoik dan monopolis ini tentu mengakibatkan sebuah tata dunia yang timpang. Tata dunia yang ditandai oleh ketidakadilan sosial dan makin merebaknya kemiskinan. Sebuah tata dunia yang menghasilkan jurang dan celah yang begitu lebar antara yang kaya dan yang miskin. Menurut Noreena, globalisasi neoliberal ini jelas lebih banyak menghasilkan ‘mereka yang kalah’ dibandingkan dengan mereka yang menang. Kesaksian Noreena atas kemiskinan dan ketimpangan yang juga terjadi di Amerika dan Inggris menjadi bukti bahwa neoliberalisme memang ancaman besar bagi dunia. Korporasi multinasional ini tiba-tiba berkembang menjadi finance oligarchy yang bersiap-siap untuk melucuti demokrasi dan keadilan sosial. Bahkan, tak segan-segan, untuk menegakkan prinsip-prinsip neoliberalisme, kekerasan juga dihalalkan dan rezim otoriter pun juga didukung asalkan menegakkan prinsip-prinip demokrasi pasar dan neoliberalisme, maka tentu juga akan tetap didukung. Yang penting, akumulasi modal dan penumpukan laba jalan terus. Begitulah ceritanya. Di negara-negara yang dulunya dipimpin oleh rejim otoriter seperti Indonesia, Argentina, Rusia, Korea Selatan atau Brazilia, neoliberalisme masuk ketika negara-negara itu mengalami krisis politik dan krisis ekonomi. Pada masa itulah melalui sejumlah agen-agen utamanya semisal IMF dan World Bank, agenda neoliberalisme mulai masuk dan membuat sejumlah penyesuaian struktural. Dan disambutlah sebuah jaman yang seringkali disebut-sebut dengan nada optimis yang meluap: transisi menuju demokrasi.
Tetapi, kita sebaiknya tidak menelan mentah-mentah sebuah doktrin bahwa setelah rejim otoriter runtuh, maka demokrasi akan menjelang, kesejahteraan dan keadilan pasti akan datang. Faktanya, ada kekuasaan lain yang jauh lebih imperalistik dan menindas. Sebuah kekuasaan korporasi yang senantiasa mengincar jalan yang sedang ditempuh oleh negara-negara yang mengalami masa transisi. Jadi, di negara-negara manapun perjalanan transisi bukan berjalan secara alami, netral dan bukan tidak ada kepentingan-kepentingan modal yang mengincar setiap ruas jalannya.
Logika demokrasi liberal yang bermain dalam konstruksi politik. Menurut Ferran Requejo (1991) logika dasar dari demokrasi liberal ialah rasionalisme. Dari sinilah, kemudian demokrasi berdiaspora menuju dataran “liberalisme” yang lebih luas. Salah satunya, diaspora logika demokrasi liberal ini membentuk karakter politik marketisme, yang cenderung mengabaikan fitrah loyalitas kepada konstituen-nya. Dalam bentuk ini juga, maka political individualism menguat dan menggantikan political society. Pada tahap yang lebih maju, demokrasi liberal akan dengan sendirinya memangkas core komunalitas dalam politik.
Hilangnya tapak komunalisme dalam demokrasi, menandaskan perbagai keyakinan akan rasionalisme dalam demokrasi; politisi pun dengan alaminya memunggut rasionalisme sebagai patronase tindakan dan pola berpolitik. Rasionalisme dalam demokrasi tetap akan dimaknai secara tidak berbeda dalam pemaknaan rasionalisme pada wilayah ekonomi. Ferran Requejo memahami rasionalisme dalam politik adalah “the maximization of particular interests of individuals and groups.” Menuju maksimalisasi keinginan, kepuasan politik; dalam hal ini ialah kekuasaan adalah semangat dari rasionalitas politik di tengah kubangan demokrasi liberal. Ini merupakan pengertian dalam bentuk yang lain dari rasionalisme pada kehidupan politik.
Rasionalisme dalam demokrasi memang tidak begitu akrab diperdengarkan dan amat jarang dikaitkan. Karena selama ini, stigma rasionalisme hanya dilekatkan pada economic an sich. Namun seiring himpitan budaya pasar, maka rasionalisme pun memasuki wilayah kehidupan secara luas, termasuk wilayah demokrasi. Inilah yang membuat kita terpaksa mencacah liberalisme dalam demokrasi. Seiring menguatnya rasionalisme dalam demokrasi menjadikan Kita sering bertanya apa pengaruh terhebat rasionalisme terhadap demokrasi.
Pecahnya rasionalisme dalam tubuh demokrasi liberal, menyebabkan gesture demokrasi berubah seketika. Hal ini dilihat dari pergeseran orientasi politik di Indonesia saat ini. Politik tidak lagi bermakna bagi khalayak, terutama bagi aktor politik sebagai upaya mendorong transisi kekuasaan ke bentuk yang aplikatif dari komitmen kebangsaan dan kerakyatan. Yang terjadi malah sebaliknya. Politik hanya mampu mendorong perubahan pada kualitas individual semata dan tidak bersentuhan sama sekali dengan bangsa.
Fungsi politik dalam demokrasi sesungguhnya untuk mendorong demokratisasi. Namun ketika dentuman liberalisme pecah dalam tubuh politik sebagai akibat lansung terkooptasinya demokrasi oleh liberalisme seketika politik berubah makna menjadi tujuan individual. Dalam kondisi ini, politik melahirkan berbagai bentuk politik semu, berupa politik pencitraan, politik digitalisasi, parahnya budaya politik uang menjadi bagian yang tak ter-elakkan.
Setiap aktor politik dikendalikan oleh mesin politik untuk berpacu menjadi authistik. Mereka mengkonstruksi realitas, yang sama sekali tidak berkaitan dengan realitas yang dialami masyarakat. Alhasil, ketimpangan ideologi dalam proses politik terhujam hebat. Ujungnya, demokrasi menjadi tumpul karena hanya dipahami sebagai fabricated kekuasaan, tak lebih.
Immediasi Politik
Meminjam istilah Kierkegaard immediasi dimaknai sebagai wilayah, di mana orang hidup berdasarkan hasrat dan perasaan yang menuntut untuk dipenuhi lansung. Ini tepat dipasangkan dengan kata politik. Karena kini tak ubahnya, realitas politik hanya dikonstruksi untuk memenuhi hasrat berkuasa secara cepat, instan, tanpa perlu mengabdi dan berbuat untuk rakyat terlebih dahulu.
Mengamati realitas politik yang sedang berkembang, mengingatkan “Kita” pada sebuah drama faust karya penyair Jerman, Goethe. Dalam drama ini diceritakan bahwa faust membuat perjanjian dengan setan agar dapat memperoleh kenikmatan, kekuasaan, dan pengetahuan yang luas, termasuk mengenal sulap. Dalam konteks ini Faust merupakan tokoh estetis, yang selalu ingin tumbuh secara instan. Apa kaitannya penggalan ini dengan realitas politik kita saat ini?
Tak ada yang menyanggal bahwa politik “Kita” saat ini lahir dari berbagai bentuk perjanjian yang kompleks, dan melibatkan banyak jejaring. Faktanya, perjanjian aktor politik dengan kekuatan modal untuk mendapatkan talangan kampanye, atau pun perjanjian politisi dengan media massa/elektronik untuk membentuk politik realitas; perjanjian-perjanjian ini adalah bagian penting dari proses politik saat ini. Ini merupakan perjanjian yang dilakukan oleh aktor politik dengan kekuatan yang berada di luar dirinya. Kemudian perjanjian-perjanjian ini akan melahirkan pelbagai konsekwesi, aneka tawaran regulasi terhadap “patner” politiknya ketika sang aktor memenangkan pertarungan politik.
Perjanjian para politisi dengan jejaring kompleks, berakibat pada muara politik hanya untuk kekuasaan spasial, bahkan amat artifisial. Tak heran jika banyak regulasi yang digubah oleh aktor politik tatkala berkuasa hanya mampu melahirkan berbagai proteksi untuk kelompok. Jika regulasi ini tak mampu membayar “utang politik”, maka seketika “pikiran liar” (the savage mind) menyertai pola dan tingkah politisi di Senayan, makanya “Kita” tak lebih terperanjat ketika banyak Dewan Rakyat (DPR) tersandung korupsi kelas kakap.
Immediasi politik ibarat sebidang tanah penuh tanaman yang semuanya ingin tumbuh. Kendati, antara satu tumbuhan tidak memiliki kualitas yang lebih dibanding yang lainnya. Demikian jua, dengan politisi kita hari ini. Pertarungan simbolik menjadi keniscayaan dari immediasi politik ini. Tak terbanyangkan bagaimana 38 parpol nasional dan enam di tingkat lokal untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saling perang bracnmark (baca; simbol) politik. Pada saat yang sama, partai-partai lama, khususnya lima besar hasil Pemilu 2004, bersanding dan bertarung satu sama lain, dipersengit dengan hadirnya “pemain” baru. Persaingan simbolik ini (baik simbol agama maupun nonagama) memperteguh pengertian masyarakat terhadap aktor politik/mesin politik “hanya segitukah kualitas politik kita”.
Demokrasi liberal yang melahirkan anak haram immediasi politik akan membuat Indonesia semakin kupak. Kenyataannya, proliferasi persaingan politik secara simbolik kian menyeret simbol primordial, agama, ideologi ke dalam medan pendangkalan makna yang cepat. Bahkan, agama, dan kata sakti nasionalisme mengalami pendangkalan akibat penetrasi politik. Ketika kalimat-kalimat sakral ini mengalami pendangkalan entah kepada apalagi kita mentransedenkan bangsa ini. Sebab kalimat agama tidak lagi menjadi sakti, sama halnya dengan kalimat nasionalisme yang tidak lagi ampuh merekat.
Transisi Menuju Demokrasi
Salah satu buku babon yang seringkali dirujuk untuk mendalami transisi adalah karya Guillermo O’Donnel, Transisi Menuju Demokrasi, yang mengungkapkan beberapa kasus transisi demokrasi di Amerika Latin dan Eropa Selatan. Buku yang terdiri dari empat volume tersebut menjelaskan bahwa transisi demokrasi paling tidak dicirikan oleh suatu peralihan dari rejim otoritarian, baik yang berbentuk rejim otoriter birokratik, otoriter populis, maupun otoriter tradisionalis, menuju rejim yang lebih demokratis. Dalam karya itu, transisi yang ideal, menurut karya Guillermo O’Donnel, terletak pada pertama, model transisi politik yang berujung pada konsolidasi demokrasi, partisipasi politik, peranan partai politik yang kian meluas, adanya demiliterisasi dan liberalisasi ekonomi. Kedua, model transisi yang tidak diwarnai oleh sebuah kecenderungan revolusioner, yang berpotensi mengembalikan suatu negara ke rejim otoritarian. Ketiga, peranan faktor-faktor internasional yang seringkali mempromosikan demokrasi. Bagi O’Donnel, faktor-faktor internasional ini cenderung bernilai positif dalam pembangunan demokratisasi di sebuah negara.
Dalam konteks yang sama, maka definisi demokratisasi yang ideal bagi masa transisi ini digambarkan oleh Adam Przeworski sebagai sebuah mekanisme institusionalisasi (pelembagaan) dari konflik yang berkelanjutan dan pelembagaan demokrasi yang mencakup cita-cita partisipasi dari seluruh kelompok yang berbeda cita-cita, kepentingan dan bahkan ideologi sekalipun dan memastikan agar semua kelompok itu bertanding dan berkontestasi dalam ‘ring’ dan mekanisme demokrasi itu.
Dalam buku Malapetaka Demokrasi Pasar (Resistbook, 2005), Coen Husain Pontoh, dengan perspektif yang berbeda, mengatakan bagaimana kekuatan modal dan faktor internasional justru merupakan faktor dominan yang menyebabkan masa transisi berbelok arah. Tidak lagi transisi menuju demokrasi, melainkan transisi menuju neoliberalisme—atau yang disebutnya sebagai transition via internationalization. Sebuah model transisi yang dipandu oleh negara-negara maju melalui hutang luar negeri, sebuah gaya transisi yang juga disokong oleh lembaga keuangan internasional semacam IMF dan World Bank. Intinya adalah sebuah transisi yang mengajak sebuah bangsa untuk menuju neoliberalisme. Melalui pembedahan atas kasus Rusia dan Argentina, Coen hendak mengingatkan bahwa model transisi yang mengarah pada neoliberalisme pada dasarnya adalah sebuah perangkap yang justru akan memenjarakan demokrasi rakyat, mengabaikan hak-haknya dan lantas meluncurkannya pada jurang krisis yang tak kunjung usai.
Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.
Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis).
Sejarah telah usai,” teriak Francis Fukuyama. Seruan itu tepat didengungkan setelah komunisme di Uni Sovyet runtuh lewat program glasnost dan perestroika dan hampir bersamaan dengannya China juga mulai membuka ekonomi nasionalnya. Komunisme dan model ekonomi-terpimpin yang awalnya begitu gagah dan tangguh melawan kapitalisme dan demokrasi liberal, tiba-tiba jatuh tersungkur tak bangkit lagi. Perang Dingin usai sudah. Lewat seruan Fukuyama itu genderang kemenangan sudah ditabuh. Hingga kini, Demokrasi Liberal dan Kapitalisme menjadi pemenang tunggal peradaban. Lantas, seperti Fukuyama ungkapkan, tugas manusia modern menjadi semakin ironis; hanya merawat dunia yang laksana museum tambo. Tidak ada lagi gairah, perlawanan dan antidot. Cerita tentang sosok Che sang petualang revolusi sudah harus dikubur dalam-dalam. Kisah heroik Lenin hanya tinggal sejarah di buku-buku, keberanian Usamah bin Laden cukup hanya tersemat di kaos-kaos anak muda saja. Narasi besar tentang revolusi dan perlawanan massa hendak diakhiri, tetapi narasi besar yang lain, yang berwujud demokrasi liberal dan kapitalisme harus tetap dibiarkan melenggang. Lantas seorang sastrawan Indonesia, Gunawan Mohamad, mengamininya dengan menuliskan sebuah buku; Setelah Revolusi Tak Ada Lagi.
Benarkah Demokrasi Liberal dan kapitalisme adalah satu-satunya kebenaran? Benarkah tidak akan ada perlawanan terhadap dominasi “Two Towers” (baca: demokrasi liberal dan kapitalisme) ini? Benarkah ini sistem yang terbaik? Benarkah kapitalisme dan demokrasi liberal tidak akan mengalami krisis dan kontradiksi internalnya?
Petaka Demokrasi Liberal
Krisis dan kritik terhadap model demokrasi liberal sebenarnya sudah jauh hari diingatkan oleh beberapa kalangan. Kritik terhadap demokrasi datang dari tradisi Marxisme – utamanya Lenin – yang menyebut bahwa demokrasi sebenarnya adalah siasat kaum borjuis. Lenin mengolok demokrasi liberal sebagai kediktatoran kaum borjuis (the dictatorship of borguise), dimana instrumen dan sumberdaya kekuasaan yang berupa hukum, ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir kelompok borjuis saja. Karena itu, alih-alih berpihak kepada kesejahteraan proletar, model demokrasi ini hanya akan menghasilkan model politik massa mengambang serta lahirnya oligarkh dan teknokrat politik yang enggan berbaur dan menjawab tuntutan serta penderitaan rakyat.
Tidak hanya pada tradisi marxisme, kritik terhadap demokrasi liberal juga datang dari kalangan pendukungnya sendiri. Ironi ini bermula dari teoretisi demokrasi Joseph Schumpeter yang menafsirkan demokrasi hanya terbatas sebagai mekanisme memilih pemimpin melalui pemilu yang kompetitif dan adil. Senada dengan itu, Samuel P. Huntington, sama naifnya dengan Schumpeter, juga menyanyikan nada yang seirama. Bagi Huntington, kualitas demokrasi diukur oleh pemilihan umum yang kompetitif, adil, jujur dan berkala dan partisipasi rakyat yang tinggi selama pemilu. Cita-cita mulia demokrasi direduksi menjadi sebatas hal yang prosedural dan teknis. Akibatnya, demokrasi hanya diwujudkan dalam pemilu. Suara rakyat dibutuhkan dan ditambang hanya ketika pemilu datang. Setelah itu, suara rakyat ditendang dan dikhianati; kebijakan publik tidak lagi memihak rakyat, harga-harga semakin mahal, penggusuran dimana-mana, BBM dinaikkan, pendidikan dan kesehatan dikomersialisasikan, kemiskinan dan pengangguran tetap saja berkembang biak. Demokrasi, dalam cita-cita yang sesungguhnya, perlahan-lahan mati.
Dalam konteks ini kritik Geoff Mulgan terhadap paradoks demokrasi sangat tepat dan jitu. Ada tiga hal pokok dalam kritiknya terhadap demokrasi. Pertama, demokrasi cenderung melahirkan oligarki dan teknokrasi. Bagaimana mungkin tuntutan rakyat banyak bisa diwakili dan digantikan oleh segelintir orang yang menilai politik sebagai karier untuk menambang keuntungan finansial?
Kedua, prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, kebebasan dan kompetisi juga telah dibajak oleh kekuatan modal. Yang disebut keterbukaan, hanya berarti keterbukaan untuk berusaha bagi pemilik modal besar, kebebasan artinya kebebasan untuk berinvestasi bagi perusahaan multinasional, kompetisi dimaknai sebagai persaingan pasar bebas yang penuh tipu daya.
Ketiga, media yang mereduksi partisipasi rakyat. Kelihaian media mengemas opini publik membuat moralitas politik menjadi abu-abu, juga cenderung menggantikan partisipasi rakyat. Ini berujung pada semakin kecil dan terpinggirkannya ‘partisipasi langsung’ dan ‘kedaulatan langsung’ rakyat.
Tidak hanya itu, sesat pikir kaum demokrasi prosedural juga karena ia menyembunyikan fakta tentang negara dan kekuasaan. Negara, seperti kita semua maklum, adalah tempat akses dan relasi ekonomi, politik, hukum berlangsung. Karena itu, sistem demokrasi juga berhadapan dengan masalah ekonomi. Negara dan sistem demokrasi juga berhubungan dengan masalah bagaimana menciptakan kesejahteraan, bagaimana menjalankan dan mengatur finansial sebuah negara. Karena itu negara membutuhkan sebuah persekutuan yang taktis dan cepat. Karena hanya model ekonomi kapitalisme yang tersedia – yang bertumpu pada kekuatan modal besar -, maka demokrasi membutuhkan kapitalisme, begitu juga sebaliknya. Dari sini, persekutuan najis itu mulai tercipta.
Di ujung jalan, tampaknya kapitalismelah yang berkuasa. Atas nama kemajuan dan perdagangan bebas, ia mulai mengangkangi negara. Atas nama pertumbuhan ekonomi, ia mulai menyiasati demokrasi. Lalu muncullah makhluk lama dengan baju yang baru: neoliberalisme. Sebuah makhluk yang mengendap-endap muncul, lalu menjalankan taktik “silent takeover”. Istilah terakhir ini dipinjam dari Noreena Heertz, artinya kurang lebih sebuah penjajahan yang terselubung.
Teror Neoliberalisme
Pada awalnya hanyalah gagasan. Neoliberalisme digulirkan sekelompok intelektual di sebuah dataran tinggi Mont Pelerin di Swiss. Beberapa pemikir, pengusaha dan media ini memperbincangkan dan mengangankan sebuah tata dunia baru yang tanpa tapal batas; sebuah tata dunia baru yang dikendalikan sepenuhnya oleh pasar dan kekuatan modal; sebuah tata dunia yang berjalan tanpa aturan negara; sebuah tata dunia yang meninggalkan negara kesejahteraan a la Keynessian menuju pasar bebas. Neoliberalisme kemudian dikenal sebagai sebuah kendaraan yang mengusung satu proyek besar dunia; globalisasi. Gagasan ini kemudian dengan cepat menjadi sebuah ‘horor global’ ketika ia diadopsi menjadi sebuah tata dunia baru. Ini terjadi setelah administrasi Reagen dan Tatcher mengadopsi gagasan Mont Pelerin Society ini. Setelah itu, hampir semua kebijakan dan lembaga internasional seperti World Bank, IMF dan WTO praktis mengalami perubahan untuk mendukung paham globalisasi.
Paling tidak, ada dua faktor yang mendorong kenapa gagasan tentang neoliberalisme ini dipakai dan diadopsi oleh rejim anglo-america tersebut. Pertama, ada krisis besar dan resesi ekonomi dunia yang utamanya mengenai Amerika Serikat. Krisis ini semacam krisis overproduksi yang menimpa sejumlah perusahaan multinasional dan perbankan yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme negara yang dianut oleh kebanyakan negara-negara dunia ketiga dan negara-negara miskin. Kedua, model negara kesejahteraan (welfare state) mengalami kebangkrutan akibat besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara untuk jaminan sosialnya rakyatnya.
Dengan demikian, kemenangan gagasan neoliberalisme adalah kemenangan bagi perusahaan multinasional dan sejumlah korporasi yang merasa menderita pada jaman kapitalisme negara. Termasuk juga kemenangan bagi negara maju dan sejumlah korporasinya untuk memberi ‘tekanan’ pada negara miskin agar mematuhi doktrin khas neoliberal: liberalisasi-privatisai-deregulasi. Pendeknya setelah jaman globalisasi neoliberal menjelang, maka tapak-tapak imperialisme ini mulai berjalan. Ini bisa ditandai oleh semakin mengguritanya korporasi internasional yang bersiap mencengkeram seluruh kehidupan rakyat.
Noreena Hertz punya gambaran yang menarik, bagaimana suasana yang terjadi setelah dunia berada dalam jaman globalisasi neoliberal ini. Menurutnya, selama berlangsungnya era globalisasi yang ditandai oleh kebijakan privatisasi, deregulasi dan liberalisasi perdagangan, dan kemajuan teknologi komunikasi, terjadi pergeseran kekuasaan. Kekuasaan pasar dan korporasi global tiba-tiba tumbuh mejadi monster yang bisa mengancam keberadaan negara dan demokrasi rakyat.
Dalam data yang dimiliki oleh Noreena tercatat ada 100 perusahaan multinasional terbesar mengontrol 20% aset asing global, 51 dari 100 negara terbesar dunia adalah perusahaan, hanya 49 yang merupakan negara bangsa. Penjualan General Motor dan Ford lebih besar daripada GDP seluruh negara-negara sub-sahara Afrika. Aset IBM, BP dan General Electric lebih besar daripada kebanyakan negara-negara kecil; dan Wal-Mart, pengecer supermarket Amerika Serikat, memiliki penghasilan yang lebih besar daripada negara-negara Eropa Timur dan Tengah termasuk Polandia, Republik Ceko, Ukraina, Hungaria, Rumania dan Slovakia. Karena itu barang-barang yang dikonsumsi manusia hampir berada dalam genggaman korporasi ini. Di tangan mereka-lah kehidupan dunia kini dipertaruhkan.
Kekuasaan korporasi yang sangat hegemoik dan monopolis ini tentu mengakibatkan sebuah tata dunia yang timpang. Tata dunia yang ditandai oleh ketidakadilan sosial dan makin merebaknya kemiskinan. Sebuah tata dunia yang menghasilkan jurang dan celah yang begitu lebar antara yang kaya dan yang miskin. Menurut Noreena, globalisasi neoliberal ini jelas lebih banyak menghasilkan ‘mereka yang kalah’ dibandingkan dengan mereka yang menang. Kesaksian Noreena atas kemiskinan dan ketimpangan yang juga terjadi di Amerika dan Inggris menjadi bukti bahwa neoliberalisme memang ancaman besar bagi dunia. Korporasi multinasional ini tiba-tiba berkembang menjadi finance oligarchy yang bersiap-siap untuk melucuti demokrasi dan keadilan sosial. Bahkan, tak segan-segan, untuk menegakkan prinsip-prinsip neoliberalisme, kekerasan juga dihalalkan dan rezim otoriter pun juga didukung asalkan menegakkan prinsip-prinip demokrasi pasar dan neoliberalisme, maka tentu juga akan tetap didukung. Yang penting, akumulasi modal dan penumpukan laba jalan terus. Begitulah ceritanya. Di negara-negara yang dulunya dipimpin oleh rejim otoriter seperti Indonesia, Argentina, Rusia, Korea Selatan atau Brazilia, neoliberalisme masuk ketika negara-negara itu mengalami krisis politik dan krisis ekonomi. Pada masa itulah melalui sejumlah agen-agen utamanya semisal IMF dan World Bank, agenda neoliberalisme mulai masuk dan membuat sejumlah penyesuaian struktural. Dan disambutlah sebuah jaman yang seringkali disebut-sebut dengan nada optimis yang meluap: transisi menuju demokrasi.
Tetapi, kita sebaiknya tidak menelan mentah-mentah sebuah doktrin bahwa setelah rejim otoriter runtuh, maka demokrasi akan menjelang, kesejahteraan dan keadilan pasti akan datang. Faktanya, ada kekuasaan lain yang jauh lebih imperalistik dan menindas. Sebuah kekuasaan korporasi yang senantiasa mengincar jalan yang sedang ditempuh oleh negara-negara yang mengalami masa transisi. Jadi, di negara-negara manapun perjalanan transisi bukan berjalan secara alami, netral dan bukan tidak ada kepentingan-kepentingan modal yang mengincar setiap ruas jalannya.
Logika demokrasi liberal yang bermain dalam konstruksi politik. Menurut Ferran Requejo (1991) logika dasar dari demokrasi liberal ialah rasionalisme. Dari sinilah, kemudian demokrasi berdiaspora menuju dataran “liberalisme” yang lebih luas. Salah satunya, diaspora logika demokrasi liberal ini membentuk karakter politik marketisme, yang cenderung mengabaikan fitrah loyalitas kepada konstituen-nya. Dalam bentuk ini juga, maka political individualism menguat dan menggantikan political society. Pada tahap yang lebih maju, demokrasi liberal akan dengan sendirinya memangkas core komunalitas dalam politik.
Hilangnya tapak komunalisme dalam demokrasi, menandaskan perbagai keyakinan akan rasionalisme dalam demokrasi; politisi pun dengan alaminya memunggut rasionalisme sebagai patronase tindakan dan pola berpolitik. Rasionalisme dalam demokrasi tetap akan dimaknai secara tidak berbeda dalam pemaknaan rasionalisme pada wilayah ekonomi. Ferran Requejo memahami rasionalisme dalam politik adalah “the maximization of particular interests of individuals and groups.” Menuju maksimalisasi keinginan, kepuasan politik; dalam hal ini ialah kekuasaan adalah semangat dari rasionalitas politik di tengah kubangan demokrasi liberal. Ini merupakan pengertian dalam bentuk yang lain dari rasionalisme pada kehidupan politik.
Rasionalisme dalam demokrasi memang tidak begitu akrab diperdengarkan dan amat jarang dikaitkan. Karena selama ini, stigma rasionalisme hanya dilekatkan pada economic an sich. Namun seiring himpitan budaya pasar, maka rasionalisme pun memasuki wilayah kehidupan secara luas, termasuk wilayah demokrasi. Inilah yang membuat kita terpaksa mencacah liberalisme dalam demokrasi. Seiring menguatnya rasionalisme dalam demokrasi menjadikan Kita sering bertanya apa pengaruh terhebat rasionalisme terhadap demokrasi.
Pecahnya rasionalisme dalam tubuh demokrasi liberal, menyebabkan gesture demokrasi berubah seketika. Hal ini dilihat dari pergeseran orientasi politik di Indonesia saat ini. Politik tidak lagi bermakna bagi khalayak, terutama bagi aktor politik sebagai upaya mendorong transisi kekuasaan ke bentuk yang aplikatif dari komitmen kebangsaan dan kerakyatan. Yang terjadi malah sebaliknya. Politik hanya mampu mendorong perubahan pada kualitas individual semata dan tidak bersentuhan sama sekali dengan bangsa.
Fungsi politik dalam demokrasi sesungguhnya untuk mendorong demokratisasi. Namun ketika dentuman liberalisme pecah dalam tubuh politik sebagai akibat lansung terkooptasinya demokrasi oleh liberalisme seketika politik berubah makna menjadi tujuan individual. Dalam kondisi ini, politik melahirkan berbagai bentuk politik semu, berupa politik pencitraan, politik digitalisasi, parahnya budaya politik uang menjadi bagian yang tak ter-elakkan.
Setiap aktor politik dikendalikan oleh mesin politik untuk berpacu menjadi authistik. Mereka mengkonstruksi realitas, yang sama sekali tidak berkaitan dengan realitas yang dialami masyarakat. Alhasil, ketimpangan ideologi dalam proses politik terhujam hebat. Ujungnya, demokrasi menjadi tumpul karena hanya dipahami sebagai fabricated kekuasaan, tak lebih.
Immediasi Politik
Meminjam istilah Kierkegaard immediasi dimaknai sebagai wilayah, di mana orang hidup berdasarkan hasrat dan perasaan yang menuntut untuk dipenuhi lansung. Ini tepat dipasangkan dengan kata politik. Karena kini tak ubahnya, realitas politik hanya dikonstruksi untuk memenuhi hasrat berkuasa secara cepat, instan, tanpa perlu mengabdi dan berbuat untuk rakyat terlebih dahulu.
Mengamati realitas politik yang sedang berkembang, mengingatkan “Kita” pada sebuah drama faust karya penyair Jerman, Goethe. Dalam drama ini diceritakan bahwa faust membuat perjanjian dengan setan agar dapat memperoleh kenikmatan, kekuasaan, dan pengetahuan yang luas, termasuk mengenal sulap. Dalam konteks ini Faust merupakan tokoh estetis, yang selalu ingin tumbuh secara instan. Apa kaitannya penggalan ini dengan realitas politik kita saat ini?
Tak ada yang menyanggal bahwa politik “Kita” saat ini lahir dari berbagai bentuk perjanjian yang kompleks, dan melibatkan banyak jejaring. Faktanya, perjanjian aktor politik dengan kekuatan modal untuk mendapatkan talangan kampanye, atau pun perjanjian politisi dengan media massa/elektronik untuk membentuk politik realitas; perjanjian-perjanjian ini adalah bagian penting dari proses politik saat ini. Ini merupakan perjanjian yang dilakukan oleh aktor politik dengan kekuatan yang berada di luar dirinya. Kemudian perjanjian-perjanjian ini akan melahirkan pelbagai konsekwesi, aneka tawaran regulasi terhadap “patner” politiknya ketika sang aktor memenangkan pertarungan politik.
Perjanjian para politisi dengan jejaring kompleks, berakibat pada muara politik hanya untuk kekuasaan spasial, bahkan amat artifisial. Tak heran jika banyak regulasi yang digubah oleh aktor politik tatkala berkuasa hanya mampu melahirkan berbagai proteksi untuk kelompok. Jika regulasi ini tak mampu membayar “utang politik”, maka seketika “pikiran liar” (the savage mind) menyertai pola dan tingkah politisi di Senayan, makanya “Kita” tak lebih terperanjat ketika banyak Dewan Rakyat (DPR) tersandung korupsi kelas kakap.
Immediasi politik ibarat sebidang tanah penuh tanaman yang semuanya ingin tumbuh. Kendati, antara satu tumbuhan tidak memiliki kualitas yang lebih dibanding yang lainnya. Demikian jua, dengan politisi kita hari ini. Pertarungan simbolik menjadi keniscayaan dari immediasi politik ini. Tak terbanyangkan bagaimana 38 parpol nasional dan enam di tingkat lokal untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saling perang bracnmark (baca; simbol) politik. Pada saat yang sama, partai-partai lama, khususnya lima besar hasil Pemilu 2004, bersanding dan bertarung satu sama lain, dipersengit dengan hadirnya “pemain” baru. Persaingan simbolik ini (baik simbol agama maupun nonagama) memperteguh pengertian masyarakat terhadap aktor politik/mesin politik “hanya segitukah kualitas politik kita”.
Demokrasi liberal yang melahirkan anak haram immediasi politik akan membuat Indonesia semakin kupak. Kenyataannya, proliferasi persaingan politik secara simbolik kian menyeret simbol primordial, agama, ideologi ke dalam medan pendangkalan makna yang cepat. Bahkan, agama, dan kata sakti nasionalisme mengalami pendangkalan akibat penetrasi politik. Ketika kalimat-kalimat sakral ini mengalami pendangkalan entah kepada apalagi kita mentransedenkan bangsa ini. Sebab kalimat agama tidak lagi menjadi sakti, sama halnya dengan kalimat nasionalisme yang tidak lagi ampuh merekat.
Transisi Menuju Demokrasi
Salah satu buku babon yang seringkali dirujuk untuk mendalami transisi adalah karya Guillermo O’Donnel, Transisi Menuju Demokrasi, yang mengungkapkan beberapa kasus transisi demokrasi di Amerika Latin dan Eropa Selatan. Buku yang terdiri dari empat volume tersebut menjelaskan bahwa transisi demokrasi paling tidak dicirikan oleh suatu peralihan dari rejim otoritarian, baik yang berbentuk rejim otoriter birokratik, otoriter populis, maupun otoriter tradisionalis, menuju rejim yang lebih demokratis. Dalam karya itu, transisi yang ideal, menurut karya Guillermo O’Donnel, terletak pada pertama, model transisi politik yang berujung pada konsolidasi demokrasi, partisipasi politik, peranan partai politik yang kian meluas, adanya demiliterisasi dan liberalisasi ekonomi. Kedua, model transisi yang tidak diwarnai oleh sebuah kecenderungan revolusioner, yang berpotensi mengembalikan suatu negara ke rejim otoritarian. Ketiga, peranan faktor-faktor internasional yang seringkali mempromosikan demokrasi. Bagi O’Donnel, faktor-faktor internasional ini cenderung bernilai positif dalam pembangunan demokratisasi di sebuah negara.
Dalam konteks yang sama, maka definisi demokratisasi yang ideal bagi masa transisi ini digambarkan oleh Adam Przeworski sebagai sebuah mekanisme institusionalisasi (pelembagaan) dari konflik yang berkelanjutan dan pelembagaan demokrasi yang mencakup cita-cita partisipasi dari seluruh kelompok yang berbeda cita-cita, kepentingan dan bahkan ideologi sekalipun dan memastikan agar semua kelompok itu bertanding dan berkontestasi dalam ‘ring’ dan mekanisme demokrasi itu.
Dalam buku Malapetaka Demokrasi Pasar (Resistbook, 2005), Coen Husain Pontoh, dengan perspektif yang berbeda, mengatakan bagaimana kekuatan modal dan faktor internasional justru merupakan faktor dominan yang menyebabkan masa transisi berbelok arah. Tidak lagi transisi menuju demokrasi, melainkan transisi menuju neoliberalisme—atau yang disebutnya sebagai transition via internationalization. Sebuah model transisi yang dipandu oleh negara-negara maju melalui hutang luar negeri, sebuah gaya transisi yang juga disokong oleh lembaga keuangan internasional semacam IMF dan World Bank. Intinya adalah sebuah transisi yang mengajak sebuah bangsa untuk menuju neoliberalisme. Melalui pembedahan atas kasus Rusia dan Argentina, Coen hendak mengingatkan bahwa model transisi yang mengarah pada neoliberalisme pada dasarnya adalah sebuah perangkap yang justru akan memenjarakan demokrasi rakyat, mengabaikan hak-haknya dan lantas meluncurkannya pada jurang krisis yang tak kunjung usai.
- Sumber:
- [You must be registered and logged in to see this link.]

 Indeks
Indeks